
Tajuk: Amerika
Oleh: Ridhwan Saidi
Terbitan: Moka Mocha Ink
Tahun: 2011
Sinopsis:
Murshid Merican, seorang anak muda Kuala Lumpur, mengharungi kota dan riwayatnya secara eksistensialis dan terbuka tanpa ikatan adat lapuk, menjumpai indah dan buruknya, kaya dan miskinnya, cinta dan bencinya, malaikat dan syaitannya, hanya untuk meneladani cita-citanya melihat kotanya berubah secara total suatu hari nanti. Dan suatu hari itu sampai dalam bentuk prasedar yang Murshid sendiri tidak akan sedari.
Rasa:
Saya mengaku, membaca novel ini, pertama kalilah saya ketemu dengan sebuah novel Malaysia yang benar-benar sedar ditulis dan diceritakan tentang "kotanya" (mengambil ideal simbolisme filem Manhattan Woody Allen, yang juga menceritakan kota cintanya, New York, yang turut dinyatakan dalam novel ini), setelanjang dan sejujur yang mungkin. Jika ada, setakat ini, sayembara penulisan tema "Kuala Lumpur" (yang pernah dibuat DBKL dan DBP 20 tahun dahulu), saya akan memenangkan novel ini sebagai juaranya.
Dalam novel ini, tiga kota (mungkin lebih, tetapi yang lain lebih kepada latar, walaupun penting) diutarakan "nafas" dan "sifat"nya; Kuala Lumpur, Miami dan New York. Murshid, protagonis yang menggerakkan "cerita" di dalam nafas tiga kota ini memperlihatkan "hidup nafas" Kuala Lumpur dan isinya - kemudian, impian "utopia" supaya Kuala Lumpur "dekat seperti New York" (dan hal ini disengajakan berkali-kali, dengan membawa pembaca masuk ke tayangan filem lucah dua lesbian berlatar kota New York, ini eskapisme Murshid yang akan mengganggu kontinum ala Jacob's Laddernya di akhir cerita), suatu kota yang "paling cocok dan mengikut hatinurani" buat Murshid (dan bukan seperti Los Angeles), dan akhirnya, Miami, suatu kota yang (sebenarnya) paling dekat dengan Kuala Lumpur dalam lanskap mata Murshid apabila kotanya "wujud" dalam satu impian yang palsu dan ditandai oleh manusia-manusia pendatang asing dan minoriti hitam (yang secara biadab Ridhwan memanggil mereka negro dalam novel ini) yang memberinya nafas setiap hari. Ini ditambah dengan perwatakan Murshid yang persis tajuk utama Utusan Malaysia 24 Oktober 2011, sebagai narator yang menceritakan setiap selirat dan tubuh telanjang Kuala Lumpur dan impian pagi dan malamnya.
Lebih menarik lagi, ia dipecahkan dalam tiga struktur, pertama Murshid dan Kuala Lumpur (dan isinya - buat saya, ini bahagian terbaik novel ini), kemudian plot penerbangan Murshid ke Miami secara terburu-buru ala-ala pengintip merangkap refugi terbela, lantas akhirnya Murshid "terbangun dari mimpi" lantas ketemu dengan sahabatnya Awang yang sudah meninggal dalam plot sebelumnya dan menyedari bagaimana "mimpi" yang dialaminya itu (seperti kata kawannya) adalah "petanda" (sign/prophercy) masa depan yang akan dihadapinya nanti. Pada mulanya, saya ingin menyumpah Ridhwan kerana berani memberi sesuatu yang klise (berkenaan bangun dari mimpi) dalam penceritaan fiksyen. Tetapi dengan penerangan panjang Ridhwan berkenaan persahabatan Murshid, Awang dan Ramlee sewaktu UiTM (kita anggap sebagai Murshid yang muda sebelum bekerja di Kuala Lumpur), dan kemudian, memberi satu lagi kejutan sureal, dengan keberanian, membawa kita lebih jauh daripada itu iaitu memasuki alam "barzakh"(?) atau alam "mati sebelum hidup semua", saya merasakan "kitaran" yang mulanya kelihatan moralis (kerana mematikan suatu utopia yang terlalu bebas dan hedonis buat konsensus tempatan) menjadi kitaran yang mempunyai makna yang "segar" sekali gus radikal: ia memohon pembaca mengitar alam ketidaksedaran ini untuk "mengitar diri" kita bagaimana kita melihat diri kita terhadap ruang dan kontinum yang sudah tersedia di hadapan (di sini, ruangnya, kota, yang boleh dikaitkan dengan negara). Adakah kita masih lagi "tuli" dan "mati" atau kita mahu "hidup" dan "sedar"? Ridhwan memohon kita melakukan "revolusi", bukan lagi "reformasi". Sifat "subversif" Ridhwan kini lebih "refine" dan tidak sekasar Cekik.
Segala aroma, sakit dan kotornya Kuala Lumpur digambar secara teliti dan menarik, juga beberapa kota yang dijadikan sebagai "perbandingan" dengan "jiwa kosong" Kuala Lumpur. Memang, Ridhwan atau Murshid mengimpikan keAmerikaan (kebaratan, pandang barat, suatu kemunafikan masyarakat kita yang memandang ke barat dan segalanya kebaratan. Rujuk hlm. 169 bila Murshid mengenakan cermin mata hitam lantas penyelubungan keAmerikaannya sempurna bila pekedai itu berkata, "This is you."), tetapi kita menyedari, Kekuala Lumpuran itu juga yang "membaham"nya akhirnya, mahu tidak mahu, palsu atau menjengkelkan, dalam bentuk bendera ataupun kematian dihempap dada bangunannya. Ini membuatkan kisah ini perlu ditelusuri sekali lagi dan sekali lagi untuk membuka setiap ikatan lapisannya. Baik membenci atau menyanjungi tuhan-tuhan barat yang dinyatakan oleh Ridhwan di dalam novel ini.
Ridhwan juga ada "mengenakan" beberapa hal sekeliling, sastera mutakhir dan keengganan elitis sastera kita untuk merubah. Juga beberapa sindiran yang sinikal terhadap Ramlee Awang Murshid yang disengajakan (sebagai wakil utama novel popular tempatan, seperti adanya Jeffery Archer untuk negara Barat). Inilah "pendapat" kulit novel terkini Ridhwan, jika kalian membaca novel popular, kalian hanya nampak lapik baju dan kulitnya. Membaca novel ini, kalian melihat tisu dan urat sarafnya secara telanjang, dan inilah "kebenaran" yang menyakitkan dan cantik buat Ridhwan.
Saya juga menyedari, setiap cerita yang diadakan dalam novel kali ini, juga tidak "lari" daripada cerita-cerita dan watak-watak yang ada dalam Cekik. Ini adalah kerana Ridhwan, sebagai seorang sasterawan, "menulis daripada pengalaman", yang memang, kita ketemu pun "suara biografi"nya dalam tulisan ini yang kelihatan lebih jelas menyerupai kisah hidupnya (kita tahu ini kerana Murshid sendiri menerangkan di dalam teks untuk menulis "jurnal hidup" yang lebih penting daripada kisah yang dibuat-buat, merujuk fiksyen ciptaan Ramlee Awang Murshid). Kita tahu Awang itu "Jimi/Hazimin", Ramlee itu "Ikhwan" dan Murshid itu "BinFilem/Ridhwan" yang menjadi pendukung blog Bin Filem. Maka kebanyakan tulisan dalam Amerika ini adalah "riwayat" hidup tiga mereka yang dari UiTM, yang kemudiannya memusat kepada Ridhwan dan hidupnya yang selalunya keluar dari konteks konvensional anak Melayu (atau kami panggil Melayu dari Pluto, atau dahulunya, Melayu hilang adat, atau semangat Hang Jebat), yang boleh kita jumpa imejannya dalam filpen-filpennya (rujuk filpen-filpen awalnya), nostalgianya terhadap Penjara Pudu dan pengalamannya di Festival Filem Miami. Ridhwan "mencatat" kesemua pengalaman ini secara mata naif, dan ini kelihatan menyinar baik dalam pengalaman-pengalamannya di Miami.
Hanya mungkin, secara keseluruhan, masih ada lagi lompong yang saya sedari adalah kerana, kali ini, Ridhwan tidak "bereditor" (bukan seperti Cekik) yang mana kali ini Ridhwan melakukan segalanya dengan sendiri. Banyak kesalahan pruf yang menyebabkan, jika anda tidak sabar, buku ini boleh sahaja dicampak sejauh 500 meter kerana kemalasan Ridhwan untuk meneliti tanda sengkang yang terlalu banyak dalam satu halaman, yang kadang-kala berpurata 20 lebih. Kemudian saya ingin menyoal jika Ridhwan ini sengaja atau tidak sengaja merosakkan tatabahasa dengan penggunaan ramai orang-orang dan kata ganti nama "aku" dan "saya". Ini terserlah "hilariously silly" bila kita membaca di hlm. 151 sewaktu Murshid di Miami:
Serius, saya tergelak cikai membaca ayat polos ini. Seakan Murshid makan banyak babi semasa di Miami.
Beberapa bahagian juga kelihatan jengkel apabila dialog yang diutarakan (khusus Dahlia dan Murshid) kelihatan seperti dialog-dialog filem Yusof Haslam yang ketinggalan zaman itu, sesuatu yang ironi apabila hal itulah yang ingin dipersendakan oleh Ridhwan (menolah konvensi dan sikap ketinggalan zaman). Dalam bahagian ketiga novel ini, sewaktu perbincangan berkenaan "arkitekstur", penulisan Ridhwan mula memasuki detik "kering", sehingga saya membaca dengan menguap dan membidas "watever" walaupun ianya mempunyai makna terhadap "arkitekstur" kota yang ditelanjangkan. Kemungkinan hal ini yang Ridhwan perlu pelajar daripada sasterawan seperti Umberto Eco dengan karyanya Focoult's Pendulum, sebuah novel yang sarat teori dan perbincangan pesudosains dan falsafah tetapi semuanya berlingkar dan berselirat teguh menunjangi plot dan masih intrig untuk dibaca.
Membaca novel ini akhirnya mengingatkan saya kepada teknik Arena Wati dalam Sanderanya. Amerika yang bercerita pusat tentang kotanya, dengan gerakan "riwayat seorang budak tidak sembahyang" sebagai pembawa ceritanya sama tarfanya seperti Sandera Arena Wati yang bercerita pusat tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia dan pascanya, dengan gerakan "riwayat anak-anak merdeka". Kedua-duanya banyak bercakap-cakap, dipenuhi dengan watak-watak yang asyik bercakap dengan gerakan cerita mendatar ala jurnal kehidupan. Sekurang-kurangnya, Amerika akhirnya memberi kita satu penutupan yang cukup bulat, dan kelihatan mengharukan, membuat kita mahu menelusuri sekali lagi kisah hidup Murshid, mungkin dalam impian kita sendiri tentang bagaimana dia melihat Kuala Lumpur dalam sisi hidup semula selepas mati.
Dalam novel ini, tiga kota (mungkin lebih, tetapi yang lain lebih kepada latar, walaupun penting) diutarakan "nafas" dan "sifat"nya; Kuala Lumpur, Miami dan New York. Murshid, protagonis yang menggerakkan "cerita" di dalam nafas tiga kota ini memperlihatkan "hidup nafas" Kuala Lumpur dan isinya - kemudian, impian "utopia" supaya Kuala Lumpur "dekat seperti New York" (dan hal ini disengajakan berkali-kali, dengan membawa pembaca masuk ke tayangan filem lucah dua lesbian berlatar kota New York, ini eskapisme Murshid yang akan mengganggu kontinum ala Jacob's Laddernya di akhir cerita), suatu kota yang "paling cocok dan mengikut hatinurani" buat Murshid (dan bukan seperti Los Angeles), dan akhirnya, Miami, suatu kota yang (sebenarnya) paling dekat dengan Kuala Lumpur dalam lanskap mata Murshid apabila kotanya "wujud" dalam satu impian yang palsu dan ditandai oleh manusia-manusia pendatang asing dan minoriti hitam (yang secara biadab Ridhwan memanggil mereka negro dalam novel ini) yang memberinya nafas setiap hari. Ini ditambah dengan perwatakan Murshid yang persis tajuk utama Utusan Malaysia 24 Oktober 2011, sebagai narator yang menceritakan setiap selirat dan tubuh telanjang Kuala Lumpur dan impian pagi dan malamnya.
Lebih menarik lagi, ia dipecahkan dalam tiga struktur, pertama Murshid dan Kuala Lumpur (dan isinya - buat saya, ini bahagian terbaik novel ini), kemudian plot penerbangan Murshid ke Miami secara terburu-buru ala-ala pengintip merangkap refugi terbela, lantas akhirnya Murshid "terbangun dari mimpi" lantas ketemu dengan sahabatnya Awang yang sudah meninggal dalam plot sebelumnya dan menyedari bagaimana "mimpi" yang dialaminya itu (seperti kata kawannya) adalah "petanda" (sign/prophercy) masa depan yang akan dihadapinya nanti. Pada mulanya, saya ingin menyumpah Ridhwan kerana berani memberi sesuatu yang klise (berkenaan bangun dari mimpi) dalam penceritaan fiksyen. Tetapi dengan penerangan panjang Ridhwan berkenaan persahabatan Murshid, Awang dan Ramlee sewaktu UiTM (kita anggap sebagai Murshid yang muda sebelum bekerja di Kuala Lumpur), dan kemudian, memberi satu lagi kejutan sureal, dengan keberanian, membawa kita lebih jauh daripada itu iaitu memasuki alam "barzakh"(?) atau alam "mati sebelum hidup semua", saya merasakan "kitaran" yang mulanya kelihatan moralis (kerana mematikan suatu utopia yang terlalu bebas dan hedonis buat konsensus tempatan) menjadi kitaran yang mempunyai makna yang "segar" sekali gus radikal: ia memohon pembaca mengitar alam ketidaksedaran ini untuk "mengitar diri" kita bagaimana kita melihat diri kita terhadap ruang dan kontinum yang sudah tersedia di hadapan (di sini, ruangnya, kota, yang boleh dikaitkan dengan negara). Adakah kita masih lagi "tuli" dan "mati" atau kita mahu "hidup" dan "sedar"? Ridhwan memohon kita melakukan "revolusi", bukan lagi "reformasi". Sifat "subversif" Ridhwan kini lebih "refine" dan tidak sekasar Cekik.
Segala aroma, sakit dan kotornya Kuala Lumpur digambar secara teliti dan menarik, juga beberapa kota yang dijadikan sebagai "perbandingan" dengan "jiwa kosong" Kuala Lumpur. Memang, Ridhwan atau Murshid mengimpikan keAmerikaan (kebaratan, pandang barat, suatu kemunafikan masyarakat kita yang memandang ke barat dan segalanya kebaratan. Rujuk hlm. 169 bila Murshid mengenakan cermin mata hitam lantas penyelubungan keAmerikaannya sempurna bila pekedai itu berkata, "This is you."), tetapi kita menyedari, Kekuala Lumpuran itu juga yang "membaham"nya akhirnya, mahu tidak mahu, palsu atau menjengkelkan, dalam bentuk bendera ataupun kematian dihempap dada bangunannya. Ini membuatkan kisah ini perlu ditelusuri sekali lagi dan sekali lagi untuk membuka setiap ikatan lapisannya. Baik membenci atau menyanjungi tuhan-tuhan barat yang dinyatakan oleh Ridhwan di dalam novel ini.
Ridhwan juga ada "mengenakan" beberapa hal sekeliling, sastera mutakhir dan keengganan elitis sastera kita untuk merubah. Juga beberapa sindiran yang sinikal terhadap Ramlee Awang Murshid yang disengajakan (sebagai wakil utama novel popular tempatan, seperti adanya Jeffery Archer untuk negara Barat). Inilah "pendapat" kulit novel terkini Ridhwan, jika kalian membaca novel popular, kalian hanya nampak lapik baju dan kulitnya. Membaca novel ini, kalian melihat tisu dan urat sarafnya secara telanjang, dan inilah "kebenaran" yang menyakitkan dan cantik buat Ridhwan.
Saya juga menyedari, setiap cerita yang diadakan dalam novel kali ini, juga tidak "lari" daripada cerita-cerita dan watak-watak yang ada dalam Cekik. Ini adalah kerana Ridhwan, sebagai seorang sasterawan, "menulis daripada pengalaman", yang memang, kita ketemu pun "suara biografi"nya dalam tulisan ini yang kelihatan lebih jelas menyerupai kisah hidupnya (kita tahu ini kerana Murshid sendiri menerangkan di dalam teks untuk menulis "jurnal hidup" yang lebih penting daripada kisah yang dibuat-buat, merujuk fiksyen ciptaan Ramlee Awang Murshid). Kita tahu Awang itu "Jimi/Hazimin", Ramlee itu "Ikhwan" dan Murshid itu "BinFilem/Ridhwan" yang menjadi pendukung blog Bin Filem. Maka kebanyakan tulisan dalam Amerika ini adalah "riwayat" hidup tiga mereka yang dari UiTM, yang kemudiannya memusat kepada Ridhwan dan hidupnya yang selalunya keluar dari konteks konvensional anak Melayu (atau kami panggil Melayu dari Pluto, atau dahulunya, Melayu hilang adat, atau semangat Hang Jebat), yang boleh kita jumpa imejannya dalam filpen-filpennya (rujuk filpen-filpen awalnya), nostalgianya terhadap Penjara Pudu dan pengalamannya di Festival Filem Miami. Ridhwan "mencatat" kesemua pengalaman ini secara mata naif, dan ini kelihatan menyinar baik dalam pengalaman-pengalamannya di Miami.
Hanya mungkin, secara keseluruhan, masih ada lagi lompong yang saya sedari adalah kerana, kali ini, Ridhwan tidak "bereditor" (bukan seperti Cekik) yang mana kali ini Ridhwan melakukan segalanya dengan sendiri. Banyak kesalahan pruf yang menyebabkan, jika anda tidak sabar, buku ini boleh sahaja dicampak sejauh 500 meter kerana kemalasan Ridhwan untuk meneliti tanda sengkang yang terlalu banyak dalam satu halaman, yang kadang-kala berpurata 20 lebih. Kemudian saya ingin menyoal jika Ridhwan ini sengaja atau tidak sengaja merosakkan tatabahasa dengan penggunaan ramai orang-orang dan kata ganti nama "aku" dan "saya". Ini terserlah "hilariously silly" bila kita membaca di hlm. 151 sewaktu Murshid di Miami:
Aku makan sandwich Cuba sebenar saya.
Serius, saya tergelak cikai membaca ayat polos ini. Seakan Murshid makan banyak babi semasa di Miami.
Beberapa bahagian juga kelihatan jengkel apabila dialog yang diutarakan (khusus Dahlia dan Murshid) kelihatan seperti dialog-dialog filem Yusof Haslam yang ketinggalan zaman itu, sesuatu yang ironi apabila hal itulah yang ingin dipersendakan oleh Ridhwan (menolah konvensi dan sikap ketinggalan zaman). Dalam bahagian ketiga novel ini, sewaktu perbincangan berkenaan "arkitekstur", penulisan Ridhwan mula memasuki detik "kering", sehingga saya membaca dengan menguap dan membidas "watever" walaupun ianya mempunyai makna terhadap "arkitekstur" kota yang ditelanjangkan. Kemungkinan hal ini yang Ridhwan perlu pelajar daripada sasterawan seperti Umberto Eco dengan karyanya Focoult's Pendulum, sebuah novel yang sarat teori dan perbincangan pesudosains dan falsafah tetapi semuanya berlingkar dan berselirat teguh menunjangi plot dan masih intrig untuk dibaca.
Membaca novel ini akhirnya mengingatkan saya kepada teknik Arena Wati dalam Sanderanya. Amerika yang bercerita pusat tentang kotanya, dengan gerakan "riwayat seorang budak tidak sembahyang" sebagai pembawa ceritanya sama tarfanya seperti Sandera Arena Wati yang bercerita pusat tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia dan pascanya, dengan gerakan "riwayat anak-anak merdeka". Kedua-duanya banyak bercakap-cakap, dipenuhi dengan watak-watak yang asyik bercakap dengan gerakan cerita mendatar ala jurnal kehidupan. Sekurang-kurangnya, Amerika akhirnya memberi kita satu penutupan yang cukup bulat, dan kelihatan mengharukan, membuat kita mahu menelusuri sekali lagi kisah hidup Murshid, mungkin dalam impian kita sendiri tentang bagaimana dia melihat Kuala Lumpur dalam sisi hidup semula selepas mati.




















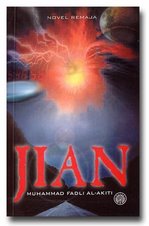
5 comments:
aku baru dapatkan buku nih kat UYA.lepas baca aku akan bg review.
telanjang telanjang.
ingat ayat tu superb sangat ke?
We can see how wide the commentar's thinking, macam kat atas ni.
Tak pernah nampaklah buku ni.
aaa abole cari kat pesta buku nanti
Post a Comment