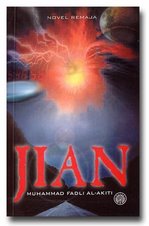Tajuk: Penyeberang SempadanOleh: Anwar Ridhwan
Terbitan: Utusan Publications & ITBM
Tahun: 2012
Sinopsis:
Quay, anak Melayu sebelum Tanah Melayu dijajah Jepun yang memakai pelbagai wajah pejuang, menyeberang sempadan zaman dan ideologi, mencari kebenaran dan pembalasan dendam, yang akhirnya, mencari diri sendiri.
Rasa:
Novel Sasterawan Negara Anwar Ridhwan yang memenangi Hadiah Sako (pertama). Anwar menggunakan kehebatannya, yang pertama, memahami dunia Melayu, kedua memahami dunia pensejagatan, dan ketiga, penggunaan teknik naratif yang unik untuk menyampaikan kisah yang biasanya ditolak sebagai risque dalam penulisan fiksyen pensejarahan Malaysia: perjuangan komunis. Hal ini mungkin pernah dan telah dilakukan Tash Aw, dan ada disentuh oleh beberapa penulis tempatan, malah disampaikan sebagai plot besar dalam Rahsia Malam Merdeka, namun dalam tangan Anwar, kisah ini disampaikan dalam bayangan besar dan maksud yang besar, suatu perjalanan yang mengambil sikap yang bukan sahaja fizikal mengubah Quay, protagonis anti-hero novel ini, tetapi psikologi dan dengan jelas, rohani.
Sikap suara benar terpendam (dan perumpamaan rohani) Quay ini, disampaikan secara licik melalui deria "bau", disampaikan sebagai penanda (dalam psikoanalisis, kita maksudkan hal ini sebagai superego) yang "mengikuti" Quay. Persoalan ini jelas: mengapa bau busuk mayat? Hal ini sahaja sudah dibayang-bayangkan, walaupun Anwar tidak pula menelusurinya secara falsafah. Hal inilah yang tampak kurang dalam novel ini, suatu perjalanan falsafah, lebih daripada fizikal yang dibentuk oleh teks. Memang imej-imej ciptaan Anwar indah dan mempesonakan, dramanya kuat dan gerakannya mantap. Namun kita, para pembaca menghausi suatu wacana diri Quay yang jelas menginginkan suatu "suara" yang perlu memahami maksud bau, maksud ideologi, dan maksud perubahan yang dilaluinya. Memang, aksi penting, namun kita seakan, dan kadang-kala terasa tertipu dengan kelancaran dari plot ke plot Anwar menyusun jejak langkah Quay dengan naif dan lurus.
Terdapat beberapa dialog, khususnya dengan sang wanita Palestin, Shafi'aa yang jelas memaparkan kenaifan ini. Dengan sekali bincang dan tanpa perlu fikir panjang, Quay melepaskan segala-galanya "untuk Islam". Memang, ya, latar, kefahaman ideologi dan plot sebelum sudah disusun bijak oleh Anwar sebagai "mencetuskan" perubahan Quay, namun kita serasa memerlukan lebih daripada itu, dan ini memerlukan kata-kata yang lebih mendalam dan memahami. Novel tulisan Alexander Solzhenitsyn yang dibeli oleh Quay, misalnya, disebut-sebut tetapi tidak pernah disentuh semangatnya. Suaranya tidak disampaikan oleh mata dan lidah Quay. Hal ini sama juga dengan sikap Quay yang terus memilih untuk ke Amerika ("loncat bas" kata orang ke Chow Kit) dengan amat mudah di Kaherah, tanpa menyedari konsikuensi dan degup getirnya, walaupun Anwar selepas itu memberikan pembaca suatu kejutan yang mengasyikkan, berkenaan dengan CIA dan penelitian mereka terhadap Quay.
Quay kiranya, dan sebenarnya, suatu watak berperwatakan yang lemah. Walaupun jelas kita mahukan "fantasi kotemporari" perjalanan (yang juga membayangkan sejarah ideologi perjalanan penulisan Malaysia sedari Asas 50) itu terhala ke sikap utopia "Islam", kita terkesima dengan cepatnya Quay berubah bentuk, seakan-akan sumpah-sumpah. Ada sesuatu yang ketinggalan dan tidak dapat diertikan, namun hal ini menyebabkan Quay hanya suatu enigma yang dikumpul untuk mengisi suatu ruang untuk penceritaan, tidak lebih daripada itu.
Namun begitu, bahasa dan gaya Anwar padat dan tepat pada setiap ruang dan masa. Penjelmaan ini jelas indah dalam pelbagai suara dan kata yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan secara lalu, dan terletak kepada pembaca untuk membacanya secara sayap kanan mahupun kiri. Ya, terdapat isu menarik yang diangkat, walaupun secara lalu, seperti "tempat kawalan" Mat Indera, pergerakan strategi Parti Komunis Malaya, cara penyiasatan Malaysia, cara hidup Komunis di China dan Rusia (babak Quay hendak membeli novel Alexander Solzhenitsyn amat menarik dan menjadi juak jelas menayangkan hipokrisi sistem ideologi pemerintahan di mana-mana pun dan bentuk apa-apa pun), dan Quay mendepani genggaman Israel terhadap Palestin pada 1970-an. Semua ini membuka dan dikupas, kelopak demi kelopak dengan baik, malah suatu suara ngeri (thriller) telah digunakan oleh Anwar untuk menggerakkan saga hidup Quay dan keluarganya. Saya sendiri paling kagum dengan bab Quay sewaktu di China, dengan penggunaan objek cengkerik sebagai simbolisme hidupnya juga sebagai maksud dia untuk keluar dari negara itu. Tulisan Anwar ini menyampaikan kehebatan suara sarwajagat dalam naratif dan sememangnya mendalam dan humanis. Puitis dan terususunnya pula dengan jelas, disampaikan dengan berkesan sekali buat saya, dalam Bab 8, babak ibunya yang meninggal dunia. Suara Anwar di sini mencapai puncaknya.
Dengan logik penyakit jiwa Quay, Anwar berjaya membawa Quay dan pembaca melangkah ke pelbagai benua dan ideologi, membujuk diri ini agar meneliti "dunia orang lain" untuk menjumpai dunia "sendiri". Anwar bukan sahaja mencipta "sejarah baharu" berkenaan bagaimana kita melihat sejarah lalu tetapi pandangan baharu untuk bagaimana kita mengekalkan sejarah yang kita ada. Yang kita pegang. Yang akhirnya, kita juga akan menemui diri kita sendiri di dalamnya. Tumpah darah. Daging dan isi.